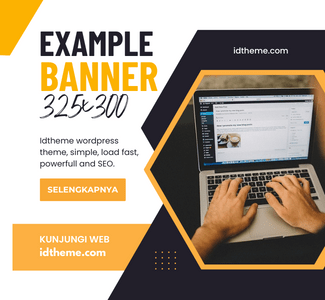Delapan puluh tahun sudah Indonesia merdeka sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan seharusnya dimaknai sebagai kebebasan dari penindasan, kesempatan yang setara dalam mengelola sumber daya, serta jaminan keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima Pancasila. Namun, dalam praktik tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam, pertanyaan besar muncul: benarkah kemerdekaan sudah dirasakan seluruh rakyat, atau justru hanya segelintir elit dan korporasi besar yang menikmatinya?
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini semestinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah (RPJP/M). Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya: tata ruang sering dipakai untuk melegitimasi alih fungsi lahan demi kepentingan korporasi, sementara rakyat kecil terpinggirkan.
Kasus pelanggaran tata ruang terjadi di banyak daerah. Di Subak Jatiluwih, Bali—yang sudah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia—muncul bangunan ilegal yang merusak zona hijau. Di Sidoarjo, kawasan pertanian berubah jadi perumahan. Konflik yang lebih besar terjadi di proyek strategis nasional, perkebunan sawit, tambang, hingga kawasan industri. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2023 mencatat ratusan konflik agraria dengan luasan lebih dari 500 ribu hektar, mayoritas melibatkan perusahaan besar berhadapan dengan masyarakat adat atau petani kecil.
Fenomena ini memperlihatkan kegagalan negara menegakkan keadilan spasial (spatial justice). Kebijakan tata ruang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan investor, sementara aspek lingkungan serta hak masyarakat diabaikan. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja justru memperkuat arah kebijakan pro-investasi dengan mempermudah izin usaha, meski sering mengorbankan partisipasi masyarakat.
Delapan dekade setelah merdeka, pola kolonialisme tampak berulang. Bedanya, aktor perampas ruang kini bukan lagi penjajah asing, melainkan elit politik-ekonomi dalam negeri yang berkolaborasi dengan korporasi transnasional. Inilah yang disebut banyak akademisi sebagai “kolonialisme internal”: rakyat tetap tersisih, kehilangan ruang hidup, dan terasing dari janji kemerdekaan.
Padahal, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang sudah mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW. Namun, partisipasi itu kerap hanya formalitas. Aspirasi rakyat jarang benar-benar didengar, sementara keputusan akhir tetap berpihak pada investor. Alhasil, perencanaan ruang menjadi top-down dan eksklusif, jauh dari prinsip perencanaan kolaboratif yang menekankan musyawarah dengan masyarakat lokal.
Peringatan 80 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum refleksi. Apakah kemerdekaan yang dirayakan setiap Agustus benar-benar substantif, atau sekadar seremonial? Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga memiliki akses adil terhadap ruang hidup dan sumber daya alam, bukan ketika segelintir elit menguasai lahan.
Oleh karena itu, ada beberapa hal mendesak yang perlu dilakukan:
- Pemerintah harus tegas menegakkan hukum tata ruang, bukan hanya pada rakyat kecil, tetapi terutama terhadap korporasi besar.
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang harus diperkuat dan dijalankan secara nyata.
- Orientasi pembangunan harus dikembalikan pada prinsip keadilan spasial dan keberlanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
- Pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan sebagai mandat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.
Kemerdekaan sejati hanya akan terwujud bila tata ruang dikelola secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil—sebagaimana amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa: sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana firman Allah: “Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya…” (QS Hud: 61).
Wallahu a’lam bisshawab.
Referensi:
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). Catatan Akhir Tahun Konflik Agraria. Jakarta: KPA.
- Healey, P. (1997). Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. London: Macmillan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.